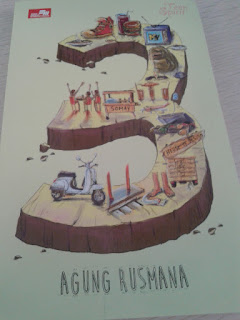Cinta ialah tentang bagaimana kekurangan bisa menjadi sumber kekuatan.
Judul buku : Kasta, Kita, Kata-Kata
Penulis : Ardila Chaka
Penyunting : Avifah Ve
Penyelaras akhir : RN
Tata sampul : Wulan Nugra
Tata isi : Violetta
Pracetak : Endang
Penerbit : PING
Terbit : 2016
Ukuran buku : 188 hlm; 13 x 19 cm
ISBN : 9786022961833
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk penerbit Divapress yang menghadiahi saya novel istimewa ini. Dan saya berusaha objektif ketika harus menceritakan kesan setelah membacanya hingga halaman terakhir.
Novel ini istimewa karena sederhana. Tema yang sederhana; persahabatan, keluarga dan sedikit bumbu cinta-cintaan. Gaya bercerita yang sederhana; menggunakan diksi yang apik percampuran bahasa puisi dan bahasa sehari-hari. Setting yang sederhana; desa wisata bernama Kalibiru dengan Waduk Sermo-nya yang menawan (saya menilai demikian setelah meng-googling). Pesan sederhana; jangan pernah patah semangat untuk belajar.
Kasta, Kita, Kata-Kata, berkisah seorang gadis 16 tahun bernama Ajeng yang memiliki gangguan bahasa afasia broca (penjelasan di halaman 49) yang dipertemukan dengan Galih, pemuda 17 tahun. Benang merahnya ditonjolkan pada perjuangan Galih membuat Ajeng bisa baca tulis, dan perjuangan Ajeng belajar agar bisa memenuhi harapan Galih dan orang tuanya.
Kasta, membahas latar belakang kedua tokoh utama yang tidak sepadan. Galih anak dari pemilik sawah yang digarap orang tua Ajeng. Sehingga perbedaan ini pun sempat mencuat menjadi konflik.
Kita, menerangkan hubungan Ajeng dan Galih yang terjalin dengan sangat murni, perasaan sederhana ingin menolong. Galih memiliki kepekaan peduli terhadap orang lain yang tinggi. Demi dilihatnya seorang Ajeng yang sering menjadi bahan omongan karena kekurangannya, Galih memutuskan membantu Ajeng belajar dengan dibantu Mbak Lia, mahasiswa KKN UGM.
Kata-Kata, salah satu poin yang kemudian menjadi pusat kedua tokoh utama bisa bersinggungan. Ajeng tidak lancar berbicara, Galih merasa terpanggil merubahnya.
Saya sangat menikmati novel ini. Jika harus saya melabelkan kata pada novel ini, indonesia dan kedaerahan adalah dua kata yang tepat. Penulis berhasil membangun situasi sebuah desa yang masih asri dengan keindahan waduknya. Saya sebagai pembaca diajak untuk membayangkan bukit Joglo dengan pemandangan Waduk Sermo. Tidak ada kemacetan, tidak ada narasi teknologi yang berlebihan, saya merasa ikut berada di sebuah kampung yang keasriaannya masih terjaga.
Selain Ajeng dan Galih, novel ini juga menghadirkan peran-peran sampingan yang ikut memberikan warna. April, adik Ajeng yang normal, cantik, supel dan pinter. Karakternya berkebalikan dengan kakaknya, Ajeng. Dia ditempatkan oleh penulis sebagai saingan Ajeng. Orang tua Galih, yang secara pola pikir sudah lebih luas ketika membicarakan soal keadaan di masyarakat Kalibiru. Kecuali untuk Bapaknya, ada penilaian pesimis terhadap pendidikan tinggi. Orang tua Ajeng, merupakan gambaran orang tua dengan pola pikir kampung yang tidak terlalu tahu hal-hal di luar kesehariannya di kampung. Namun keunggulan orang tua Ajeng terletak pada bagaimana mereka mendukung semua keputusan anak selama hal itu baik.
Plot yang digunakan penulis merupakan percampuran plot maju dan mundur. Pemilihan plot mundur yang dikemas dengan narasi, membuat novel ini tetap pada jalur mengulik perjalanan Ajeng dan Galih. Jika diceritakan dengan kemasan penceritaan seperti masa sekarang, saya punya keyakinan novel ini akan lebih tebal dan akan membuat cerita berputar-putar jauh dahulu sebelum kembali ke jalur utamanya.
Ada tiga bagian cerita yang membuat saya hampir ikut menangis. Pertama, ketika Mbak Lia harus kembali ke kota dan meninggalkan Ajeng (halaman 113 – 117). Posisi saat itu, Ajeng sudah mengalami perkembangan pesat dalam belajar membaca dan menulis. Kemajuan itu berkat kegigihan Mbak Lia juga. Hubungan mereka yang kurang dari 2 bulan tersebut telah membentuk ikatan seperti kakak adik. Ajeng merasa sedih karena dia kehilangan sosok pengajar yang hebat. Narasinya benar-benar mengharukan dan pembaca akan sangat gampang turut ikut sedih sebab pembaca sudah dijejali bagaimana Mbak Lia membimbing Ajeng.
Kedua, ketika Galih sudah kembali ke rumah setelah dirawat di rumah sakit karena kecelakaan, Bapaknya berbohong soal teman dekatnya bernama Agung (halaman 144 – 150). Saya pun akan marah kalau kekhawatiran saya pada teman baik dianggap baik-baik saja oleh Bapak, padahal teman baik saya itu sudah dimakamkan. Emosi yang muncul karena kesal, marah, sedih, bercampur dan bingung harus merasakan yang mana dulu.
Ketiga, ketika Galih akan berangkat ke sekolahnya untuk bertemu guru BK menanyakan soal beasiswanya di UGM, ia dilarang mengendarai motor oleh ibunya karena baru sembuh kecelakaan. Lalu sang Bapak muncul menawarkan diri. Ini yang paling mengharukan. Padahal Bapaknya tidak pernah setuju dengan keinginan Galih kuliah. Berminggu-minggu Galih berusaha menyampaikan niatan itu, namun sang Bapak keukeuh tidak setuju. Dan ketika akhirnya Bapak menawarkan diri mengantar Galih, itu isyarat kalau ia setuju dengan keinginan Galih kuliah. Kesabaran Galih berbuah manis.
Dan dua jempol bagi penulis yang menyisipkan bumbu cinta-cintaan untuk kedua tokoh utama tanpa merusak kesederhanaan tema lainnya. Halus sekali penulis membahas perasaan kertertarikan Ajeng pada Galih, Galih pada Ajeng. Yang akhirnya disuguhkan terang-terangan justru perasaan April pada Agung, namun justru memilukan. Mungkin penulis mempertimbangan hubungan percintaan anak muda umur 16-17 tahunan dengan setting pedesaan tidak bisa dieksplor seperti percintaan ala anak metropolitan atau kota besar lainnya. Terlalu tabu, bahkan sekedar berpelukan.
Tidak ada karya yang sempurna, begitu pun dengan novel ini. Saya masih menemukan beberapa typo yang jumlahnya tidak banyak dan tidak mengganggu proses saya membaca. Kemudian saya juga menemukan keanehan pada sifat Ajeng yang sangat polos berubah menjadi sosok yang cuek dan pengumpat di halaman 98-99.
Aku sendiri sedang tak ingin ambil pusing. (hal.98)
Sial! Aku memimpikan Galih. (hal.99)
Berikut ini beberapa kutipan menarik yang saya tandai selama membaca:
- “...Dewasa itu di pikiran, Pak....” (hal.12)
- Begitulah hidup. Selalu ada yang dibandingkan,.. (hal.22)
- Banyak batasan yang seharusnya bisa dilepaskan. (hal.29)
- ...setiap perbuatan yang dilakukan selalu dapat timbal balik. (hal.31)
- “Orang berbuat salah memang terkadang tidak terasa...” (hal.31)
- Belajar memang perlu sabar. (hal.84)
- Perpisahan harus tetap terjadi. Layaknya pertemuan yang tak terelakan. (hal.114)
- Air mata setetes justru lebih tulus dibandingkan dengan yang mengalir deras. (hal.126)
Akhirnya, saya bersyukur dijodohkan dengan novel yang istimewa ini. Banyak hal yang saya dapatkan dari cerita Ajeng dan Galih. Novel ini saya rekomendasikan untuk pembaca yang ingin menikmati bacaan dengan setting pedesaan ditambah cerita dengan nilai kemanusiaan yang benar-benar murni. Saya memberikan rating 4 dari 5 untuk Kasta, Kita, Kata-Kata.